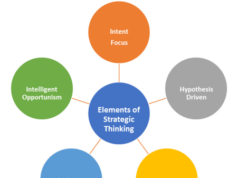Oleh: Dahlan Iskan
Sabtu 07 Juli 2018
Saya video kamar VIP istri saya. Saya kirimkan ke teman saya. Yang di Singapura. Juga yang di Tiongkok. “Benarkah itu rumah sakit di Samarinda?,” ujar mereka.
Keduanya pernah ke Samarinda. Hampir sepuluh tahun lalu. Saat Samarinda masih gelap: sering mati lampu.
”Kelihatannya lebih bagus dari kamar Anda di RS Singapura itu,” ujar teman saya yang Singapura. Dalam bahasa Inggris.
”Hahaha…lebih bagus dari kamar Anda di lantai 10 RS Tianjin …” komentar teman Tiongkok saya. Dalam bahasa Mandarin.
”Padahal tarifnya hanya 25 persennya,” jawab saya. Dengan kepala membesar.
Maka tidak menyesal saya membatalkan ini: membawa istri ke Singapura. Meski sudah terlanjur bikin janji dengan dokter di sana.
Tentu dunia kedokteran tidak boleh hanya adu penampilan fisiknya. Kualitas layanannya ikut menentukan. Juga peralatannya. Dan yang utama kualitas medikalnya.
Saya tentu tidak ingin memperjudikan istri saya. Sekedar untuk kebanggaan kampung halaman. Begitu tiba di RS Wahab Syachrani ini saya kelilingi fasilitasnya. Saya kuat-kuatkan kaki saya. Rumah sakit ini tanahnya 33 ha.
Ternyata memang jauh di atas bayangan saya: kamar operasinya 26! Rumah sakit di daerah yang dulu begitu terpencil punya OK begitu banyaknya. Dengan AC sentral.
Sudah mampu pula melakukan operasi jantung: tiap hari. Punya MRI. Punya CT scan yang 126 slice. Coba tanya di kota Anda: siapa yang punya 126 slice. Masih ada dua lagi yang di bawah itu.
Untuk kanker pun sudah punya petscan. Hanya ada empat rumah sakit di Indonesia yang memiliki petscan. Kota sebesar Surabaya pun belum punya. Bahkan belum ada rencana punya. Baru sebatas ingin punya.
Dengan petscan itu benih kanker sekecil 2 mm pun sudah bisa dideteksi. Sedangkan untuk terapinya jangan kaget: sudah punya radio nuklir. Pasien yang terkena kanker teroid diterapi radio nuklir. Lalu dimasukkan ruang isolasi selama tiga hari.
Ruang ini sangat khusus: terisolasi dari radiasi nuklir. Pembuatan ruangnya harus atas pengawasan Bapeten: badan yang bertanggung jawab untuk keamanan nuklir.
Penggunaannya juga harus seijin Bapeten. RS Wahab Syachrani Samarinda ini punya enam ruang isolasi seperti itu. Enam. Edan.
Saya pun mantap: menyerahkan istri saya pada tim dokter di kampung kelahiran istri saya itu. Yang sudah 40 tahun ditinggalkannya itu.
Saya pun berdiskusi dengan tim dokternya: dokter Boyke Soebhali, dokter Kuntjoro Yakti, dokter Satria Sewu, dokter Moh Furqon dan dokter Teddy Ferdinand Indrasutanto. Juga melihat alat yang bernama FURS: pencari posisi batu ginjal yang bisa fleksibel. Bisa belok-belok mencari di slempitan mana batu itu berada.
Dokter Rachim Dinata, sang kepala rumah sakit, hadir: memperkenalkan dokter-dokter itu. Lalu menyilahkan kami diskusi sendiri. Rachim Dinatalah di balik semua prestasi itu. Ia dokter ahli bedah. Lulusan Universitas Padjadjaran Bandung. Kini dokter Rachim telah membalik dunia: dari kuno ke modern.
Tidak hanya alat dan fisiknya. Tapi juga sistem dan SDM-nya.
Penghasilan dokter di rumah sakit ini empat kali lipat dari penghasilan dokter di rumah sakit kota saya. Dokter Rachim menyebutkan angka-angkanya. Tapi biarlah imajinasi menuliskan angkanya sendiri.
Dokter Rachim menerapkan sistem prestasi. Di atas hirarkhi. Di atas senioritas. Di atas penampilan fisik.
Dokter Boyke misalnya: lebih bertampang rocker daripada dokter. Rambutnya dibiarkan gondrong. Celananya jean. Bawaannya ransel. Mainannya gitar.
Suatu saat pasien yang sok terdidik bertanya padanya: apakah ia mahasiswa yang lagi magang. Si pasien terperanjat ketika akhirnya tahu: yang ditanya itu adalah dokter spesialis urologi.
”Ada empat dokter yang gondrong di sini,” ujar dr Nurliana Andriati Noor. ”Yang penting kegondrongannya tidak menganggu kerja dokternya,” tambah dokter Nana.
Di akhir diskusi saya putuskan: saya serahkan istri saya kepada tim dokter. Lakukan apa pun yang terbaik menurut dokter. Saya tandatangani dua pernyataan: setuju dibius total dan setuju dilakukan operasi. Jadwal ditetapkan: keesokan harinya. Jam 9 pagi.
Istri saya pernah operasi syaraf tulang belakang. Akibat HNP, 20 tahun lalu. Saya diajak Prof Hafidz Surabaya untuk ikut masuk ruang operasi. Tiga tahun lalu istri saya operasi ganti lutut. Saya diajak dokter Dwikora Surabaya ikut masuk ruang operasi. Kemarin, saya diajak dokter Boyke masuk ruang operasi.
Saya pun bisa melihat bagaimana FURS masuk ke ginjal. Lalu dibelok-belokkan. Memasuki ruang-ruang yang ada di dalam ginjal. Mencari di mana batu itu sembunyi.
Ketemu: satu batu. Lalu FURS itu diajak menjelajah ruang-ruang lain dalam ginjal. Ketemu: satu lagi. Lebih besar. Total: dua batu.
Yang satu batu lagi sudah dikeluarkan di Surabaya dua minggu lalu. Yang posisinya sudah di saluran kencing. Yang sudah bernanah. Yang menyebarkan infeksi ke seluruh tubuh. Yang membuat istri saya koma. Yang memaksa saya mendadak pulang dari Amerika.
Dokter Boyke terus menggerakkan alatnya. Diiringi lagu-lagu barat. Yang ia setel dari stock yang ada di HP-nya.
Anak ‘wedok’ saya, Isna Fitriana, mendekatkan mulutnya ke telinga saya. ”Wow… kegemaran dokter Boyke rupanya sama dengan saya: lagu-lagu Bon Jovi,” bisik anak wedok saya itu.
Ternyata dokter Boyke juga seperti anak saya itu: gemar bersepeda. Bahkan sepedanya sama: merk Wdnsdy. Baca: Wednesday. Yang diproduksi oleh Azrul Ananda. Anak sulung saya.
Oleh dokter Boyke batu yang lebih kecil itu diusik. Dipindahkan dari tempatnya. Dijadikan satu dengan batu yang lebih besar. Saya pikir mau dihancurkan bersamaan. Ternyata tidak. Hanya dibandingkan ukurannya. Lalu batu yang lebih kecil dimasukkan jaring. Yang dipasang di ujung alatnya. Jaring ditarik.
Ternyata ukuran batu itu lebih kecil dari saluran air kencing. Maka batu pun dikeluarkan. Tidak dihancurkan.
Yang besar pun kemudian dijaring. Dicoba ditarik. Ternyata lebih besar dari saluran kencing. Maka batu itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya: akan ditembak dengan laser.
Saya pikir batu itu akan langsung hancur saat dilaser. Ternyata laser itu hanya mencuil-cuil batu. Maka lasernya terus ditembakkan. Ratusan cuilan terlepas dari batu. Lama-lama batunya tinggal secuil. Menembaknya kian sulit. Cuilan terakhir itu lari-lari. Terbawa arus air yang disemprotkan: untuk mendinginkan bagian ginjal di sekitar laser yang sangat panas.
Selesai. Satu jam persis.
Cuilan-cuilan batu itu ukurannya sebutir pasir. Akan keluar bersama air kencing.
Satu jam kemudian istri saya sudah kembali di kamar yang lebih baik dari lantai 10 RS Tianjin tadi.
”Saya ingin lihat batunya,” ujar istri saya. Maka saya serahkan batu yang tidak dihancurkan tadi. Juga satu cuilan batu sebesar pasir hasil tembakan laser.
Istri saya memang sempat berharap dokter Boyke kecele: tidak menemukan batunya. Mengapa? Dua hari sebelumnya istri saya merebus kelapa hijau muda. Lalu meminum airnya. Keesokan harinya dia rebus lagi kelapa hijau muda. Diminum lagi.
Dengan cara itu dia harapkan batu bisa keluar sendiri. Seperti yang banyak dishare di media sosial.
Ternyata fakultas kedokteran tidak bisa digantikan kelapa hijau rebus.(dis)
http://disway.id/serba-ada-di-samarinda/